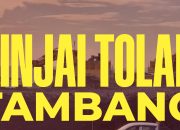OPINI, Suara Jelata— Jika boleh dikatakan, karya sastra merupakan suatu hal menyangkut fenomena kehidupan manusia yang secara garis besar seperti persoalan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia satu dengan manusia lain dalam lingkup sosial, hubungan manusia dengan alam sekitar, serta hubungan manusia dengan Tuhan.
Oleh karena itu, banyak sisi kehidupan manusia yang (dapat) dijamah oleh karya sastra, seperti halnya kesedihan, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, protes, dan pola pikir. Pun dalam lingkungan, tatanan sosial budaya, tatanan politik, ekonomi, dan sejenisnya.
Dengan demikian, karya sastra identik (walau tidak semuanya sama) dengan berita di koran, laporan penelitian, dan sejarah. Sebab karya sastra dan non sastra tersebut sama-sama berbicara tentang manusia dan hal-hal yang berhubungan dengannya.
Hal yang membedakan adalah cara penyajiannya dan (mungkin) asumsi pembaca terhadap jenis tulisan tersebut.
Cara menyajikan ‘nasib para petani’ dalam bahasa sastra akan berbeda dengan cara yang digunakan dalam bahasa non karya sastra, seperti berita, laporan penelitian dan sejenisnya.
Meskipun pada inti datanya sama-sama fakta. Demikian pula, asumsi pembaca terhadap tulisan sastra dan non sastra cenderung berbeda.
Kebanyakan pembaca berasumsi bahwa karya sastra itu selalu imaginer, fiktif, atau khayalan belaka. Sedang berita, laporan penelitian, dan sejenisnya selalu nyata dan benar adanya.
Pertanyaannya, benarkah bahwa seorang sastrawan menulis karya-karyanya tanpa berdasarkan fakta-fakta pada zamannya, atau data-data yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tulisannya bersifat fiktif atau khayalan belaka? Atau sebaliknya, apakah sejarawan, peneliti, dan reporter menulis fakta yang terjadi di lapangan secara benar-benar obyektif, independen, tanpa dipengaruhi subyektifitas, kepentingan dan cara berpikirnya?
Atau, barangkali pembaca akan mengatakan bahwa ketika tulisan sudah terjadi, baik itu karya sastra atau non sastra bisa saja mengandung unsur-unsur subyektif dan dipengaruhi oleh ideologi bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda?
Sepengetahuan penulis, orang-orang yang mengatakan bahwa karya sastra itu−walaupun bersifat imaginer, fiktif dan khayalan−tetap mengetengahkan fakta tentang kehidupan manusia dan sejumlah sisi yang menyertainya, adalah mereka yang menggeluti dalam dunia sastra.
Sementara masyarakat luas secara umum dan kalangan akademisi tertentu menganggap bahwa karya sastra adalah benar-benar bersifat imaginer, fiktif, atau hanya dunia rekaan pengarang yang kurang, atau bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan fakta dan data, seperti sejarah, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, agama, moral dan sebagainya.
Memahami karya sastra dengan cara pandang interdisipliner memungkinkan kita untuk mengetahui banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dan hal-hal berkaitan dengannya.
Interdisipliner dalam karya sastra dapat membuka sudut pandang kita pada hal yang lebih luas. Kita dapat melihat bahwa disiplin-disiplin ilmu tertentu tidak lebih unggul dari disiplin-disiplin yang lain. Sebab, setiap disiplin ilmu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam melihat fenomena kehidupan manusia.
Setiap disiplin memiliki obyek dan permasalahan yang diselesaikan dengan caranya sendiri dan tidak dapat diselesaikan ileh disiplin yang lain. Cara pandang interdisipliner dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki banyak sisi. Atau dengan kata lain, cara pandang interdisipliner dalam kasus-kasus tertentu sangat dibutuhkan, karena penjelasan yang menyeluruh terhadap fenomena yang terjadi.
Penulis ambil contoh sebuah karya sastra dalam bentuk novel yang berjudul Teror Moral, Karya Ongky Arista UA.
Dalam novel itu pengarang penggambarkan pola berlakunya sebuah moral di suatu daerah setempat. Dimana dalam daerah tersebut terdapat dua pasangan yang dipaksa menikah karena alasan menjaga moral.
Ya, moral masyarakat yang menganggap aib ketika ada pasangan kekasih ketahuan berduaan di tempat sepi, dengan alasan apapun, baik atas dasar suka sama suka atau ketidaksengajaan, pasangan tersebut yang diketahui oleh tim keamanan moral wajib dinikahkan.
Sehingga para pemuda di daerah tersebut bukan takut atau menguragi untuk tidak saling berhubungan, melainkan mencari cara agar hubungannya tidak diketahui oleh tim keamanan moral setempat.
Melihat novel Teror Moral yang diterbitkan pada tahun 2020 dapat membuka cakrawala kita bahwa dalam kehidupan masyarakat, kita sering mengambil kesimpulan tanpa mendatangkan data-data. Masyarakat kita seringkali mementingkan kesempurnaan sepihak tanpa melihat persoalannya secara keseluruhan.
Sehingga pola moral yang awalnya bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak berprilaku melenceng malah sebaliknya, menjadi momok bagi masyarakat setempat, sehingga pola kehidupan yang terjadi hamper keseluruhan terkesan mengada-ngada.
Bisa dibayangkan sosok perempuan dalam novel tersebut, berhenti tidak melakukan berbuatan hubungan terlarang karena hanya takut ketahuan oleh tim keamanan moral. Dirinya takut dinikahkan secara paksa, karena bagi masyarakat di daerah tersebut, jika ada sepasang kekasih yang dinikahkan karena ketahuan berduaan, maka pernikahannya dianggap memalukan, meskipun yang dinikahkan karena ketahuan berduaan tersebut atas dasar suka sama suka.
Suatu pandangan lain adalah menyangkut agama, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama hadir sebagai rahmat, maka seharusnya seluruh syariatnya dijalankan dengan penuh kasih sayang, bukan sebaliknya, agama seakan-akan memenjarakan penganutnya.
Dalam novel Teror Moral, seorang pimpinan keamanan moral setempat bisa-bisanya melakukan hubungan terlarang dengan waktu yang sudah lama, tapi ia tidak pernah dikenakan hukuman karena belum pernah ketahuan oleh tim keamanan moral, meskipun dirinya juga bagian dari tim keamanan moral−pimpinannya pula.
Hal ini menjadi bukti bahwa agama tidak lagi menjadi kontrol kesadaran dalam kehidupan masyarakat, melainkan agama hanya sebatas membicaraan peraturan yang selesai atas dugaan dan persepsi masyarakat.
Penulis : Ach. Jazuli, Mahasiswa Pascasarjana Unisma Malang