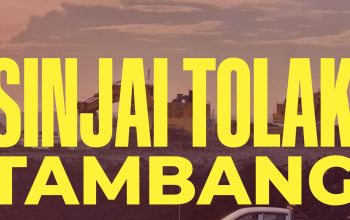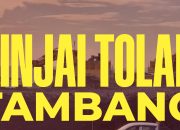OPINI, Suara Jelata —Media akhir-akhir ini tengah disibukkan dengan beberapa fenomena sebagai bentuk klimaks dari sebuah cerita yang identik dengan dramatisasi yang menegangkan sehingga mengundang segelintir tanya dari publik.
Akhir cerita dari pemilu 2019, misalnya, yang memberikan beberapa pembelajaran besar pada khalayak dari peristiwa-peristiwa yang lahir mulai dari sebab musabab kematian ratusan panitia penyelenggara pemilu, desas desus kecurangan KPU, peristiwa parlemen jalanan 21 – 22 Mei 2019 yang menelan korban jiwa hingga fenomena di balik pembatasan media sosial oleh Kemkominfo.
Semuanya tersajikan dalam bentuk pemberitaan di media nasional dan alternatif utamanya media online sampai hari ini dan tidak jarang pula isi dari pemberitaan-pemberitaan tersebut melahirkan berbagai macam pandangan bagi khalayak, pro dan kontra yang berujung perdebatan menjadi kuasa tersendiri dari penyajian informasi.
Pro dan kontra pemilu yang tersajikan melalui media kerapkali menjadi hidangan tambahan selain kopi di warung-warung kopi hingga menjalar ke pedesaan sebagai pembahasan beberapa tokoh masyarakat yang kerap berujung perdebatan antara mempertahankan kubu pilihan masing-masing dengan pembenarannya sehingga kubu yang merasa kalah melahirkan sebuah mosi tidak percaya terhadap apa yang disajikan oleh media.
Beberapa hari terakhir, fenomena hasil akhir pemilu menjadi trending topic di beberapa media dan melahirkan sebuah konstruksi pada khalayak yang tentunya mempengaruhi cara pandang.
Penyajian sebuah berita dengan konten berbeda yang memiliki tema yang sama akan melahirkan nuansa kebingungan di tubuh pembaca sehingga ketidakmampuan mendeteksi antara ‘real news dan fake news’ merupakan sebuah keniscayaan apalagi bagi pembaca yang menangkap sebuah berita berdasarkan emosional dan kepercayaan pribadi maka tidak bisa dipungkiri proses persebaran berita akan cepat tanpa memastikan benar atau tidaknya berita tersebut.
Fenomena seperti ini merupakan sebuah pemandangan keseharian di dunia maya dewasa ini yang sering atau bahkan selalu dilakukan oleh pembaca, sebuah kondisi dimana yang membentuk pandangan atau opini masyarakat lebih kepada pengaruh emosional dan kepercayaan pribadi dibanding fakta dan data yang objektif, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya proses internalisasi narasi yang dilakukan oleh pembaca.
Sementara di tubuh beberapa media sendiri, penyajian narasi dalam bentuk berita kerap mengandalkan dan memantik emosi pembaca sehingga hal demikian memancing reaksi cepat pembaca atau bahkan menyulut amarah.
Strategi pemberitaan seperti ini lebih memanfaatkan aspek emosional pembaca untuk kemudian membuka sebuah pintu menuju ke alam bawah sadar melakukan penanaman ketakutan dan kecemasan sehingga mendorong perilaku.
Selanjutnya, sebagai arena kontrol sosial dengan mengalihkan perhatian khalayak dari isu-isu penting.
Kondisi seperti itu sering pula ditemukan di permukaan, sebuah strategi pengalihan isu dengan menciptakan gangguan sehingga secara tidak langsung masyarakat diarahkan kepada isu-isu yang terbilang kurang substansial dan melupakan isu-isu krusial yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan rakyat.
Contoh kasus dari konstruksi media pada umumnya terhadap masyarakat, seorang anak yang tinggal di desa dan suatu hari memutuskan untuk melanjutkan pendidikan (kuliah) di kota.
Selain daripada pesan keteguhan dan kesungguhan untuk belajar di kota yang diperoleh dari orang tuanya, juga terdapat pesan lain yakni “jangan melakukan atau ikut demonstrasi” karena bagi orang tuanya, tindakan demonstrasi adalah sebuah bentuk kekerasan.
Hal demikian diperoleh dari beberapa media utamanya televisi, memang pada dasarnya beberapa stasiun televisi kerap menayangkan berita demonstrasi kepada para pemirsa dengan pola rekonstruksi emosi, yakni proses penataan ulang berita dengan mengedepankan penggunaan emosional bagi khalayak, misalnya demonstrasi yang dilakukan di kota metropolitan berujung kericuhan antara mahasiswa dengan aparat.
Yang ditayangkan adalah hanyalah kericuhannya bukan landasan mahasiswa melakukan demonstrasi atau tuntutan sehingga tertanam stigma pada masyarakat bahwa demonstrasi adalah sesuatu yang tidak baik, alhasil hal demikian pula akan menjadi pesan pamungkas orang tua kepada anaknya sebelum menginjakkan kaki di kota.
Contoh kasus di atas menjadi sebuah budaya tersendiri bagi beberapa orang tua di pedesaan berdasarkan analisa penulis padahal demonstrasi pada dasarnya bukanlah sebuah gerakan yang identik dengan kekerasan.
Demonstrasi merupakan sebuah tindakan terakhir yang ditempuh dari proses advokasi terhadap sebuah kebijakan publik yang dinilai bermuatan ketimpangan berdasarkan temuan dari riset advokasi yang pernah dilakukan bukan merupakan sebuah tindakan yang spontan dilakukan.
Berita yang dimuat di media kiranya penting ditelaah dengan bijaksana oleh khalayak melalui budaya analitis, kritis dan akal budi sehingga persebaran informasi yang tergolong ‘fake news’ mampu diminimalisir atau bahkan dicegah begitupula mekanisme penyajian informasi di media berdasarkan data dan fakta sehingga informasi yang disajikan mampu menjadi salah satu bentuk narasi pengembangan ilmu pengetahuan yang ilmiah bagi masyarakat luas.
Penulis: Askar Nur
– Tulisan tersebut adalah tanggung jawab penuh penulis.