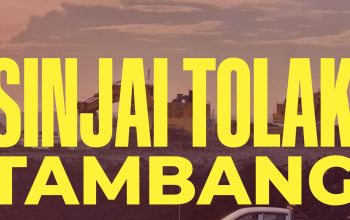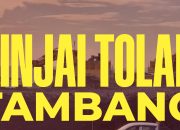OPINI, Suara Jelata— Di tengah arus besar yang melanda Indonesia belakangan ini, khususnya mengenai konservatisme keberagamaan, dimana relasi antara agama dan budaya agaknya akan menjadi persoalan yang kian akut.
Ekspresi keberagamaan di tengah masyarakat yang multiragam, sebagai konsekuensi dari pluralitas sosial seharusnya bisa dikelola dalam bingkai kemajemukan.
Di sinilah sebenarnya letak betapa pentingnya kita mengurai khususnya problem filosofis terkait relasi antara agama dan budaya. Secara sosio-antropologis, sebenarnya persinggungan antara agama dan budaya ialah sebuah keniscayaan, dimana agama sebagai sebuah “katakanlah” produk yang bersifat keilahian (divine), agama tentu diklaim sebagai seperangkat ajaran yang murni dan otentik.
Meskipun demikian, ini patut untuk diingat bahwa entitas agama yang (diklaim) murni dan otentik itu tentulah membutuhkan sarana prasarana kultural-sosiologis untuk kemudian bisa sampai pada manusia.
Dalam konteks yang inilah, persinggungan antara agama dan budaya menjadi tidak terelakkan. Maka, menjadi hal yang sangat wajar jika sebuah agama identik dengan kebudayaan masyarakat tertentu.
Misalnya Hindu yang sangat identik dengan kultur masyarakat India, Nasrani yang sangat lekat dengan kultur masyarakat Eropa atau Barat, juga Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakat Arab itu sendiri.
Dengan identifikasi inilah menurut penulis, Relasi ataupun persinggungan antara agama dan budaya tentu saja tidak terlepas dari konteks geografis (wilayah), historis (sejarah) dan sosiologis (masyarakat) dimana agama lahir atau diturunkan. Pada fase selanjutnya, ketika agama tersebar ke seluruh dunia, maka tentu tak akan terelakkan persinggungan antara kebudayaan dengan ragam entitas keberagamaan itu sendiri.
Terkait dengan relasi antara agama dan budaya itu sendiri, maka perlu kiranya untuk mengetahui relasi diantara keduanya, apakah agama ini kemudian bertentangan dengan budaya yang ada, lantas bagaimana dengan keberadaan dari agama-agama lokal itu sendiri?
Dalam konteks Indonesia yang mana merupakan negara yang majemuk dan multiragam, yang terdiri atas ribuan pulau-pulau, suku, budaya dan sebagainya. Maka tidak heran jika banyak dijumpai keberadaan agama- agama lokal (agama leluhur) di pelosok Nusantara ini, juga perlu diketahui bersama bahwasanya keberadaan agama-agama leluhur ini telah ada, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Maka dari itu, perlu kiranya khususnya bagi para pengkaji agama dan budaya untuk kemudian mengenal istilah, yakni great tradition dan little tradition yang diperkenalkan oleh antropolog Robert Redfield.
Dimana great tradition ini merujuk pada praktik keberagamaan yang merujuk kepada teks-teks keagamaan, serta lebih dekat pada tradisi asal agama tersebut muncul.
Sebagai contoh great tradition dalam Islam, dimana praktik keberagamaannya itu menjadikan Al-Qur’an, Sunnah Rasul dan tradisi masyarakat Arab sebagai sumber utama dalam menentukan hukum Islam.
Adapun pada little tradition ini merepresentasikan ekspresi keberagamaan yang mana ini sangat kental dengan budaya atau tradisi lokal, dimana masyarakat pemeluk agama tertentu tinggal. Dalam pembacaan klasifikasi dikotomis ala Redfield, little tradition ini adalah ekspresi keberagamaan kaum muslim tadi yang mana telah mengalami perjumpaan akulturatif dengan tradisi lokal yang ada di Arab sana.
Yang dalam istilah lain, menurut Komarudin Hidayat, menyebutnya sebagai ‘local genius’ atau ‘local wisdom’.
Perlu untuk diketahui sebelumnya, bahwasanya kearifan lokal itu bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga hubungan baik dengan alam yang telah memberinya banyak manfaat dalam kehidupan.
Adapun mengenai persinggungan antara ajaran agama dan kearifan lokal inilah yang kemudian melatari munculnya beragam ekspresi keberislaman yang khas masyarakat Indonesia dan nyaris tidak dapat kita temukan di wilayah muslim lainnya. Dimana corak keberislaman di Indonesia sangat lekat dengan budaya itu sendiri.
Sebagai contoh, kita akan dengan mudah menjumpai ekspresi keislaman yang sejalan dengan tradisi budaya masyarakat tertentu, misal pemakaian sarung dalam shalat atau cara membaca Al-Quran dengan langgam tembang Jawa, ataupun songkok recca yang kental akan kearifan lokal itu sendiri.
Di lain sisi, kita juga akan dengan mudah menemukan praktik-praktik kebudayaan lokal yang bersenyawa dengan ajaran agama. Seperti dapat dilihat dalam tradisi Ma’Barasanji yang dikenal hampir seluruh masyarakat muslim di Sulawesi.
Meski masih mempertahankan ritual yang penuh dengan simbol tradisi Klasik (Hindu-Budha), namun di dalamnya terselip bacaan-bacaan dari Al-Quran dan sholawat-sholawat nabi sebagai pengantar ritual.
Fenomena itu ditanggapi beragam oleh kalangan muslim, misalnya tanggapan dari kelompok konservatif-puritan, yang menganggap bahwasanya fenomena tersebut ialah sebagai sebuah bentuk sinkretisme atau pencampuradukan antara agama dan budaya.
Kebanyakan dari mereka beranggapan, masuknya tradisi dan budaya dalam agama akan mengancam kesucian atau sakralitas agama.
Sebaliknya, sebagian muslim berhaluan moderat-progresif yang pada umumnya tidak menganggap hal tersebut sebagai persoalan serius. Kelompok moderat ini yang kemudian memilih istilah akulturasi untuk menggambarkan perjumpaan antara agama dan budaya yang dalam banyak, hal keduanya ini mempengaruhi satu sama lain.
Bagi kaum muslim moderat, akulturasi agama dan budaya tidak akan mengancam sakralitas agama, alih-alih kian memperkaya khazanah keberagamaan itu sendiri.
Munculnya ekspresi keberagamaan yang multiragam merupakan konsekuensi logis dari dinamika hubungan agama dan masyarakat. Maka kiranya perlu bagi pembaca dan terkhusus bagi penulis sendiri untuk kemudian memahami bahwasanya antara agama dan budaya ini ialah dua entitas yang saling mempengaruhi satu sama lain, dimana agama membutuhkan budaya sebagai sarana pengimplementasian nilai-nilainya, sedang budaya membutuhkan agama untuk kemudian menjadi pedoman ataupun panduannya.
Akhir kata dari saya, mengutip salah satu guyonan Almarhum Gus Dur “Yang sama jangan dibeda-bedakan, dan yang beda jangan dipaksa untuk sama”.
Penulis: A.Tenri Wuleng, Ketua KOPRI Rayon Ushuluddin dan Filsafat
Tulisan tersebut diatas merupakan tanggung jawab penuh penulis